Manusia, Teknologi, dan Tuhan: Percakapan Tentang Kesadaran
Manusia, Teknologi, dan Tuhan: Percakapan Tentang Kesadaran
Pernahkah kamu duduk diam dan berpikir — untuk apa semua ini? Untuk apa manusia hidup, berlari, berharap, mencipta, lalu kembali menjadi tanah?
Pertanyaan semacam itu yang jadi awal dari percakapan panjang saya dengan seorang teman diskusi. Dari argumen tentang teknologi, kami tenggelam dalam pembahasan yang jauh lebih dalam: tentang hidup, kehendak, dan bagaimana manusia seharusnya bersikap dalam sistem semesta yang tak pernah bisa dipahami sepenuhnya.
Apakah Teknologi Membuat Manusia Lebih Bahagia?
Semua bermula dari satu pertanyaan:
"Apakah manusia akan lebih bahagia jika hidup tanpa teknologi modern?"
Saya berargumen: tidak. Teknologi membawa banyak hal baik—memperpanjang usia, memperluas akses pendidikan, menciptakan konektivitas global. Meskipun ada efek samping seperti kecanduan, stres, dan keterasingan, secara keseluruhan teknologi memperbesar pilihan dan mempercepat pertumbuhan.
Tapi teman saya menanggapi dengan cara yang tak terduga.
"Bahagia itu relatif. Segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya zero sum game—yang untung ada karena yang lain rugi, yang bahagia muncul karena yang lain tidak bahagia. Maka semua akan kembali ke netral."
Boom. Argumen langsung menggeser jalur — dari soal teknologi jadi soal hakikat kehidupan.
Netralitas dan Siklus: Apakah Hidup Itu Hanya Berjalan Saja?
Teman saya mengembangkan idenya: manusia itu seperti sel di dalam tubuh yang lebih besar. Kita hidup berdampingan dengan makhluk lain, dalam satu sistem besar yang mungkin tak bisa kita pahami, tapi tetap kita jalani. Semuanya hanyalah sesuatu yang “berjalan saja”.
Menurutnya, hidup bukan tentang bahagia atau tidak bahagia, menang atau kalah. Karena pada akhirnya, sistem semesta ini akan menyeimbangkan dirinya sendiri—dengan atau tanpa kita.
Saya membalas dengan satu pertanyaan:
“Kalau begitu, apakah manusia hanya penumpang pasif? Atau masih punya peran dalam sistem besar itu?”
Dan di sinilah arah diskusi berubah menjadi spiritual — bahkan kontemplatif.
Manusia: Penumpang Aktif Dalam Kehendak Tuhan
Menurut teman saya, manusia memang penumpang aktif. Kita punya kesadaran, bisa berpikir dan bertindak. Tapi semua tetap berada dalam arus besar kehendak Tuhan — entitas agung yang mencakup semua, baik yang hidup maupun tidak, yang tampak maupun tak tampak.
Kehidupan manusia, katanya, adalah bagian kecil dari rangkaian besar yang punya arah sendiri. Kita bisa menanam benih kehancuran, tapi semesta akan menyetir ulang jalannya. Seperti bumi yang rusak oleh manusia, lalu memulihkan dirinya sendiri melalui waktu.
“Manusia menjalani yang menurutnya terbaik dan bermanfaat untuk yang menurutnya terbaik.”
“Bukan soal hasil. Bukan soal benar atau salah. Tapi soal menjalani — dengan sadar.”
Jadi Apa Peran Doa, Harapan, dan Niat?
Kalau semuanya sudah ditentukan oleh sistem semesta atau kehendak Tuhan, lalu untuk apa manusia berdoa? Untuk apa berharap?
Menurutnya, doa dan harapan adalah ekspresi dari keterbatasan manusia. Kita berdoa bukan untuk memaksa semesta mengubah arah, tapi untuk menyelaraskan hati kita dengan kenyataan.
“Manusia yang semakin memahami kehidupan akan sangat hati-hati dalam berharap. Karena tidak semua yang menurutnya baik adalah baik, dan tidak semua yang menurutnya buruk adalah buruk.”
Orang bijak bukanlah orang yang selalu tahu ke mana harus melangkah, tapi yang tetap melangkah dengan hati-hati, sadar bahwa ia mungkin tak tahu arah sepenuhnya.
Menjadi Manusia yang Baik
Saya bertanya:
“Kalau begitu, dalam sistem besar yang tak bisa kita kendalikan ini — seperti apa sebenarnya manusia yang baik?”
Jawabannya sederhana tapi dalam:
“Manusia yang terus belajar, memahami, melakukan, mengharapkan, dan mengusahakan hal yang menurutnya baik. Atau sederhananya: manusia yang bijak dalam berpikir, berharap, dan bertindak.”
Bukan karena yakin akan berhasil. Bukan karena tahu segalanya. Tapi karena sadar bahwa proses itulah bentuk tertinggi dari kemanusiaan.
Penutup: Jalan yang Terus Mengalir
Percakapan ini tak memberikan jawaban pasti, dan memang tak perlu. Karena seperti kata Rumi:
“Kau bukan setetes air di lautan. Kau adalah seluruh lautan yang tercermin dalam setetes air.”
Kita tidak harus tahu semuanya untuk menjalani hidup dengan utuh. Kita hanya perlu sadar, terus belajar, dan menjalani peran kita — sekecil apapun — dalam harmoni besar semesta.
Terima kasih sudah membaca sampai sini.
Jika kamu merasa tulisan ini menggugah sesuatu dalam dirimu, bagikan ke orang lain. Bukan untuk menyebar “kebenaran,” tapi untuk mengajak lebih banyak orang merenung bersama.
Karena mungkin, itulah yang bisa kita lakukan — menjadi manusia yang terus belajar, menyadari, dan mengalir dalam hidup yang terus berjalan.
Catatan: Postingan ini merupakan hasil dari diskusi saya dengan AI. Dalam narasi yang dituliskan, saya berperan sebagai teman diskusi, sementara AI dituliskan seolah sebagai saya.

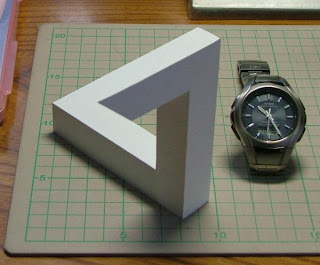
Comments
Post a Comment